08.06
08.06.
Hujan deras mengguyur sepagian ini. Lima belas menit yang lalu, si sulung baru berangkat ke sekolah, riang sekali karena akhirnya kembali bersekolah setelah tiga hari demam batuk pilek. Tak henti-hentinya dia mengoceh sedari bangun tidur. Tadi teman sebangkunya menjemput ke rumah, untuk bersama-sama jalan ke sekolah. Sementara si bungsu tertidur dalam pelukanku, setelah dari pukul empat pagi rewel karena batuk pilek. Beberapa malam belakangan, aku dan suamiku berganti-gantian menjaga si bungsu yang berkali-kali terbangun karena tak enak badan dirudung demam. Sebelumnya kukira ia mau tumbuh gigi. Kata Ibuku waktu kemarin videocall, itu tanda-tandanya bayi mau tambah kebisaan. Ternyata si bungsu cuma dapat ‘hadiah’ pilek dari kakaknya, yang terlalu gemas mencium si adik saat ingus berleleran.
Suamiku sedang melahap sarapannya, sambil memeriksa e-mail dari laptop. Katanya hari ini dia bisa masuk kantor agak siang, meski ada beberapa bahan meeting yang harus disiapkannya dari rumah.
Perlahan kuletakkan si bungsu di kasurnya. Laparku menjadi-jadi, membayangkan teh manis dan seiris roti yang sudah disiapkan oleh suamiku.
Di meja makan, teh sudah dingin, begitu pula dengan rotiku. Tak perlulah kupanaskan, aku sangat lapar. Baru saja mengunyah beberapa gigitan roti, terdengar tangisan si bungsu, melengking keras.
Aku masih lapar.
Buru-buru kujejalkan sisa potongan roti ke dalam mulut dan kutinggalkan teh manisku, untuk kembali menggendong si bungsu.
Dari jendela kamar, tampak hujan sedikit mereda. Namun langit masih gelap digayut mendung. Lampu jalanan masih menyala, redup menerangi jalan depan rumah. Kulirik jam weker di atas meja nakas.
08.17.
Kususui kembali si bungsu, sampai ia kembali tertidur. Tadi dia sedikit berontak marah, mungkin karena hidungnya kutetesi sedikit obat. Semalam napasnya kembali berbunyi grook-grookk. Sembilan tahun berselang, tiap mengurus anak yang sakit ternyata lelahnya masih sama saja, bahkan lebih. Mungkin karena faktor U juga. Umur, gitu. Malam-malam kurang tidur, ditambah lagi tenaga rasanya habis terisap tiap kali si bungsu lahap menyusu. Mencuri-curi tidur siang, kalau tak ada pekerjaan rumah yang menanti. Lalu menemani si sulung yang tiap pulang sekolah antusias bercerita tentang harinya, minta didengarkan dan dibantu bikin PR. Ada hari-hari di mana aku berharap dapat melewatinya dalam sepi. Agar tenang. Agar aku bisa mengatur napas dan mengatur isi kepalaku. Hari ini, salah satunya.
Pikiranku melayang, berusaha merunut sudah dari hari apa aku memakai baju piyama yang penuh bau susu dan muntahan ini. Kapan terakhir kali aku mandi dan keramas? Kapan terakhir kali aku jalan sendirian tanpa mendorong si bungsu dalam keretanya, yang kian hari kian terasa seperti membawa bom waktu yang bisa menjerit sewaktu-waktu? Kapan terakhir kali aku bisa duduk tenang, membaca buku kesukaanku? Kapan terakhir kali aku bisa berenang sendirian? Kapan terakhir kali aku menikmati lari pagi di tengah udara dingin?
08.35
Kuletakkan kembali si bungsu di tempat tidurnya. Kini ia sudah lebih tenang. Jam-jam segini, biasanya dia bisa tidur lebih lama, satu jam saja sudah bagus. Dua jam, dengan keajaiban Tuhan.
Aku terduduk di tepi tempat tidur. Kembali memikirkan pertanyaan barusan. Semilir angin menelisip lewat jendela yang kubuka sedikit. Dingin.
“Sayang,” bisik suamiku mengendap-endap masuk ke kamar, “Mau gantian aku gendong si Adek?”
Aku menoleh. Diam saja.
"Mau gantian aku yang gendong si Adek?”
"Pa,”
“Ya?”
“Aku mau lari.”
Gantian suamiku yang terdiam, mukanya bingung mendengar jawabanku.
“Sebentar saja. Boleh ya?”
“Nanti kamu nggak capek?”
“Aku… aku nggak sanggup mikir. Aku ingin keluar sebentar.
Jam segini, Adek biasanya tidur lebih lama kok. Tadi juga sudah kukasih obat tetes hidung.
I really need this. Aku janji, setengah jam lagi aku sudah di rumah. Kamu berangkat meeting jam 10, kan?”

08.54.
Kutarik resleting jaketku sampai ke dagu. Di weather app, suhu Bergen pagi itu sekitar 3 derajat Celsius. Kata temanku, cuma orang gila yang di tengah udara sedingin kulkas begini malah keluar lari pagi. Mungkin aku memang gila. Peduli amat. Aku butuh ini.
Konon katanya, all you need is the first step. On everything. Yang penting jalani dulu. Lakukan saja dulu. Satu langkah kuayunkan, berganti langkah lagi, dan lagi. Seketika aku merasa kembali menjadi diriku sendiri. Bukan ibu rumah tangga berpiyama kucel bau susu dan muntahan bayi. Angin menderu-deru di telingaku, begitu dingin menggigit sampai nyaris membuat hidung, mulut dan pipiku terasa mati rasa. Kupercepat langkah-langkah kakiku, selagi jalanan yang dilewati masih datar.
Paha dan betisku mulai terasa sakit setelah melewati tanjakan pertama, dekat sekolah si sulung. Tapi aku terus berlari, mengubah tumpuanku. Midfoot strike, no hunching. Atur napas.
Tanpa kusadari, sedari tadi tanganku mengepal keras. Sambil terus berlari, kubuka kepalan tangan & kukibas berkali-kali sampai agak lemas. Lalu kutempelkan ujung ibu jari ke ujung jari manis. Atur napas. We tend to hold on things way too long until it destroy us. So, just stop holding onto it.
Langkah kaki membawaku ke seberang gedung sekolah. Dari balik pagar, tampak ruang cubby dengan jejeran rak jaket murid-murid. Kulihat jaket hujan merah milik si Sulung tergantung di situ. Sedang apa Si Sulung di kelasnya? Hari ini ada pelajaran apa di jam pertama? Aku lupa memeriksa jadwal pelajaran yang dia berikan Jumat lalu. Biasanya tiap Minggu sore kubaca teliti isi jadwal pelajarannya untuk seminggu ke depan, memastikan tugas-tugas apa saja yang harus dia kerjakan sebelum hari Senin tiba. Minggu lalu, aku lupa menyiapkan botol selai untuk pelajaran prakarya si sulung. Sebelumnya, aku menerima notifikasi kalau si sulung lupa mengembalikan buku pinjaman dari perpustakaan. Untung hanya telat dua hari, belum sampai kena denda.
Saat si bungsu hadir, kuakui perhatianku untuk si sulung banyak berkurang, teralihkan untuk si bungsu. Bahkan seringkali aku makin tak sabaran menghadapi si sulung. Si sulung pun sering protes karena menurutnya, setelah ada adik, tak ada lagi bekal sushi atau nasi goreng omurice di kotak bekalnya. Plus, menurutnya, bekal buatan Papa tidak seenak buatan Mama. Pernah sekali si sulung cemburu, katanya sekarang Mama dan Papa lebih sayang sama Adek. Tidak, aku tidak pernah menuntut si sulung harus begini harus begitu ke adiknya. Menurutku, tidak adil bagi si sulung untuk dibebani tuntutan 'harus sayang harus bisa pintar mengurus adik'. Tugas mengurus anak -mau anak sulung dan bungsu- ya tugasnya orangtua, bukan tugas si anak pertama. Aku tahu, ia sangat menyayangi adiknya, meskipun seringkali terlalu gemas sampai membuat adiknya menangis. Dan aku sering juga tak sabaran menegurnya.
Seketika perasaan bersalah kembali menyerbu. She deserves a better mom.
Buru-buru kuusap wajahku.
That’s why I’m doing this. I need to feel better. I need to take care of myself. Taking care of myself is part of taking care of my kids.
Kulihat sekilas jam tanganku.
09.13.
Sebentar lagi waktu istirahat pertama. Kuteruskan saja berlari, jangan sampai keburu si sulung keluar dan menemukan mamanya berkeliaran di luar gedung sekolah. Nanti dia malu sama teman-temannya.
Tanjakan kedua. Kupaksakan untuk tetap berlari. Tenggorokanku mulai terasa perih oleh udara dingin kering. Dalam hati aku menyesal, lupa membawa botol air minum dari rumah. Apa nanti sebelum pulang, mampir dulu saja ke café untuk secangkir latte?
Akhir-akhir ini banyak sekali kulihat postingan di akun-akun bertema parenting yang menyuarakan dua istilah yang sedang in: self-care dan me-time. Katanya, ngopi-ngopi enak itu self-care: merawat diri dengan memberikan waktu untuk diri sendiri menikmati hal-hal kecil yang menyenangkan. Begitu pula dengan ke salon untuk merawat diri, shopping bersama kawan-kawan, atau menonton bioskop. Katanya, buat ibu-ibu jaman sekarang, me-time dan self-care adalah sebuah kewajiban.
Teman-temanku pun sering mengingatkan, pokoknya jangan lupa me-time dan mengurus diri. Aku tersenyum miris. Sudah berapa lama hal-hal enak tersebut jauh dari keseharianku? Tak semuanya bisa selalu kulakukan selama di sini, saat merantau bersama suami. Sabtu atau Minggu siang yang tenang saja sudah merupakan sebuah kemewahan bagi kami. Ke salon? Membayangkan harga 30 menit sesi pijat spa bisa seharga uang belanja dua minggu, aku pusing duluan. Bagiku, bisa mandi di bawah guyuran shower panas saja sudah nikmat sekali. Menonton bioskop, ah lupakan saja. Tiket nonton berdua plus sewa jasa babysitter saja sudah setara dengan uang belanja seminggu. Ngopi-ngopi enak? Aku justru lebih suka ngopi berdua suami, memulai Minggu pagi kami sebelum anak-anak terbangun. Shopping? Duh, apalagi itu. Belum juga shopping-nya dimulai, kepalaku sudah senat-senut membayangkan tagihan usai berbelanja.
Aku menghela napas. Bawah rusukku terasa sedikit nyeri, tetapi kuteruskan berlari melewati tanjakan ketiga.
Daripada pusing memikirkan hal-hal yang tak bisa kunikmati, lebih baik kunikmati apa yang bisa kulakukan. Terkadang, bukan hal-hal manis yang kita butuhkan untuk merasa lebih enakan. Siapa yang bilang lari dingin-dingin begini enak. Tetapi aku membutuhkannya. Karena untuk sesaat, aku bisa merasa bebas. Untuk sesaat, aku bisa merasa kembali menjadi diriku sendiri. Dulu pernah ada yang pernah berkomentar, kalau kesukaannku berlari itu sebenarnya karena aku ingin ‘lari dari kenyataan’. Aku hanya tersenyum. Semua orang pasti punya pelariannya masing-masing, tetapi bukan urusanku untuk menentukan pelarian seperti apa yang cocok buat orang lain. Yang kutahu, waktu umur 17, aku berlari untuk ‘melarikan diri’ dari kekecewaan tak lulus seleksi PMDK dan patah hati diputus cinta. Waktu usia 20an, aku lari untuk ‘melarikan diri’ dari kenyataan bahwa berat badanku berlebih sampai divonis susah jodoh. Kini, lebih baik selama 30 menit aku ‘lari dari kenyataan’ tetapi kemudian aku selalu pulang kembali ke rumah, merasa lebih enak.
09.22.
Sedikit lagi belokan menuju rumah sudah kelihatan. Aku berenti sejenak, terengah-engah. Tiga puluh menit, aku berjanji. Kuhirup napas dalam-dalam. A cup of hot chocolate after the run sounds good. Or maybe, a long hot shower first.
09.24.
Pahaku mulai terasa kebas. Ujung jemari tangan makin sakit karena dingin yang semakin menggigit. Mungkin kita memang butuh rasa sakit. Untuk mengingatkan diri, bahwa kita hidup di masa kini. Bukan di masa lampau, bukan juga dihabiskan untuk membayangkan hal-hal yang tak bisa dimiliki atau di luar kendali.
09.27.
Kuketuk perlahan pintu rumah. My body aches, my muscles sore. I breathe like my life depends on it.
But I feel better. Much better.

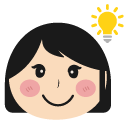




*peluk Aini*
I feel you!