Helicopter Parenting
Antara tahun 1996-2001 saya menjadi mahasiswa sekaligus juragan kos. Yang menarik, pada tahun 1990-an, anaklah yang mencari kos sendiri, tetapi setelah tahun 2000, saya lebih banyak berhadapan dengan orangtua. Para orangtua datang mencari kamar, bernegosiasi harga, bahkan mentransfer uang kos bulanan. Hari-hari di mana anak kos memberikan uang bulanan pada saya sudah tidak ada, karena keuangan mereka masih diatur orangtua.
Suatu hari ada sepasang orangtua yang datang bersama anaknya untuk mencari kamar. Mereka bahkan menuntut untuk melihat sebersih apa dapur kami. Saya bertanya, apakah si anak memiliki pantangan makan karena penyakit tertentu. Ternyata tidak ada, mereka hanya ingin meyakini kalau makanan yang disantap anaknya benar-benar bersih dan ia bisa makan dengan teratur. Anak mereka sudah berusia 18 tahun, sehat dan masuk jurusan teknik yang berpotensi harus kerja proyek tambang di lokasi terpencil. Saya setuju bahwa kita selalu mengusahakan makan teratur dan bersih. Penyedia jasa kos pun akan mengusahakannya. Namun hadapilah kenyataan, hidup jauh dari orangtua? Jadi mahasiswa dengan seabrek tugasnya? Cepat atau lambat, ia harus berhadapan dengan makanan seadanya di kampus. Lagi pula sebenarnya semua hal ini bisa ditanyakan sendiri oleh si anak. Namun tidak demikian yang terjadi. Orangtua masih turun tangan sendiri.
Pada kasus lain, ada teman saya bernama Budi (26). Suatu hari, mobil Budi tidak sengaja ditabrak tetangganya sendiri Edi (22). Yang mengejutkan, ibunya Edi yang membereskan masalah dengan Budi. Sang ibulah yang mengurus bengkel dan pembayaran urusan mobil Budi. Bahkan saat Budi ingin berbicara dengan Edi, sang ibu melarang dengan alasan toh semua sudah dibereskan. Edi yang saat itu sudah sarjana masih dilindungi oleh ibunya dari konflik.

(kredit foto: www.freedigitalphotos.net)
Helicopter Parenting
Apa yang mereka lakukan disebut sebagai helicopter parenting. Julie Lythcott-Haims dalam buku How to Raise an Adult melihat tren di kalangan orangtua golongan kelas menengah beberapa dekade terakhir yang terlalu ingin anaknya sukses. Mereka langsung mengintervensi setiap kali anak itu menemui masalah. Mereka beranggapan kalau anak akan sukses jika semua hambatan dan konflik yang memberikan kesulitan dalam hidup sang anak dihilangkan.
Di sinilah kunci masalahnya. Semua manusia memang menginginkan kemudahan. Namun dari kesulitanlah seseorang akan belajar tentang proses. Kita juga tidak akan tahu arti kerukunan dan kerja sama jika tidak pernah dihadapkan dengan konflik dan cara penyelesaiannya. Observasi yang sama juga dilakukan oleh Jessica Lahey dalam bukunya The Gift of Failure.
Tindakan helicopter parenting yang sering orangtua lakukan, berpotensi merenggut semua pembelajaran hidup dan life skill dari anak. Dalam bukunya, Lythcott-Haims menyebutkan helicopter parenting dapat menyebabkan anak tumbuh tanpa kesabaran, ketabahan menjalani proses, dan kemampuan melewati rintangan. Singkatnya, anak akan tumbuh tanpa life skill yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dewasa.
Bagaimana kita tahu sudah melakukan helicopter parenting pada anak?
Ketika anak kita ada konflik dengan anak lain di sekolah dan orangtua jadi saling berkonfrontasi.
Ketika kita terus-menerus berpikir, "Anak kita jangan pernah tersakiti hatinya dan karena itu, kita selesaikan semua konflik untuk mereka."
Ketika anak bertanya bagaimana ia harus menyelesaikan sesuatu dan malah kita yang menyelesaikannya. We solve the problem, but we fail to teach him in case it happens again in future.
Ketika kita terus-menerus berpikir "Anak kita berhak mendapatkan segalanya dan segalanya itu harus yang terbaik."
Apa Yang Bisa Kita Lakukan?
Baik Lythcott-Haims maupun Lahey dalam masing-masing buku mereka mengungkapkan bahwa anak sebaiknya dibiarkan menghadapi konfliknya sendiri, biarkan mereka menyelesaikannya.
Bagaimana kita bisa yakin mereka akan melakukan hal yang benar?
1. Tanamkan values yang diinginkan
Di rumah, kita tanamkan values yang kita inginkan—dan menjadi bekalnya saat berinteraksi di luar rumah. Contohnya: Salah ya salah, benar ya benar. Jangan salahkan yang benar dan benarkan yang salah. Jika salah, minta maaf. Jika benar tapi disalahkan, bela dirimu. Kita bisa dan harus membekali hal ini dalam diri anak, agar ia memiliki konsep yang benar dalam pikirannya sebelum keluar rumah.
2. Role Play
Ada istilah, we don’t know what we don’t know. Kita tidak akan tahu bagaimana harus bersikap jika belum menghadapi kejadiannya. Sebagai orangtua, kita dapat membantu dengan role play. Kita bisa memeragakannya pada anak, simulasi banyak kejadian. Role play yang paling sederhana seperti bagaimana jika teman menyontek, bagaimana jika ada teman yang ketinggalan bekal di rumah, bagaimana jika kita tidak sengaja menginjak kaki orang.
"Nih Mas. Ceritanya Mama jadi bully. Papa jadi Mas. Lihat ya bagaimana seharusnya kita bersikap jika kita dibully."
"Nih Kang. Ceritanya Bapak jadi temanmu yang ketinggalan uang jajan. Mama jadi kamu. Lihat ya bagaimana kita sebaiknya bersikap."
3. Evaluasi
Evaluasi setelah kejadian dapat menjadi pelajaran berharga untuk anak. Orangtua bisa melakukan ini jika orangtua berkomunikasi aktif pada anak. Tanyakan bagaimana harinya? Apakah ia berkonflik atau tidak. Apa konfliknya? Bagaimana ia menyelesaikannya? Kemudian baru kita masuk,
"Menurut kamu, reaksi kamu betul atau salah?"
"Kamu pukul dia duluan? Menurut kamu, anak yang baik memukul-mukul, atau minta maaf?"
"Kamu sudah benar kok. Tapi lain kali tahan emosinya dulu. Kalau bisa, jangan memukul duluan."
Seperti itu.
Sampai Mana Batasan Helicopter Parenting?
Ada tiga perkara di mana helicopter parenting tidak berlaku. Pertama, memberikan pendidikan terbaik. Tidak ada yang salah dengan mengusahakan rezeki untuk menyekolahkan anak setinggi langit. Kedua, mengawasi balita dari bahaya fisik—karena ia memang belum mampu menakar risiko jatuh dari pohon, misalnya. Namun bukan berarti anak umur 12 tahun masih harus kita awasi juga. Ketiga, memberikan cautionary tale yang dapat diambil pelajarannya—agar tidak perlu mereka alami.
"Papa tidak mau mengatur pergaulan SMA kamu. Tapi ingat ya, kalau sampai nge-drugs, kamu harus masuk rehab, 5 tahun hidup kamu hilang. Kamu akan susah dapat kerja. Fungsi hati kamu terganggu. Sudah ribuan kasus seperti itu. Jangan seperti itu ya."
"Mama gak mau mengawasi kamu pacaran. Tapi kamu jangan ngapa-ngapain ya. Ingat sama agama. Ingat sama dosa. Ingat juga bahwa sesungguhnya setiap orangtua, menanggung dosa anaknya juga. Jadi apa pun godaan kamu, ingat sama diri kamu. Ingat juga sama Mama."
Singkatnya, nasihat. Setelah menjadi orangtua, saya mengerti kenapa semua orangtua itu bawel. Lebih baik bawel, daripada parno dan menyelesaikan konflik anak.
Selebihnya, kita harus percaya pada anak kita untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri. Membekalkan mereka values, agar mereka berinteraksi dengan baik dengan dunia—dan di saat yang sama, merasakan baik dan buruknya perlakuan dunia (dalam skalanya sendiri di TK, SD, SMP, SMA, Kuliah).
Mengapa Ini Penting?
Percayalah, kita tidak ingin anak kita steril dari tantangan. Kita ingin anak kita imun, untuk mampu menghadapi tantangannya sendiri.

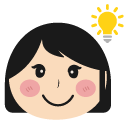




Thanks for the article kang adhit!
thanks kang adhit, seperti biasa artikel nya reminder yang bagus untuk para orang tua:)
Artikelnya bagus, spt biasa :)
Dulu suka mikir kl orgtua saya itu "tegaan" krn sering ngebiarin apa2 diselesaikan sendiri, malah sempet sebel krn "dipaksa" utk ikut pramuka.
Mungkin krn hidup di keluarga besar yg saudaranya banyak, jadi perhatian orgtua juga musti dibagi2 ke saudara yg lain. Tapi Mulai terasa banget manfaatnya stlh kuliah sampai skrg.
Thanks kang artikelnya!
Baguuuuuuuuuuus banget artikelnya, harus semangat berusaha menjadi orang tua yang baik yang bisa mendidik anak anak baik ke depannya :)
Masih terus dan terus harus belajar lagi... soalnya masih suka kelepasan nih.