Mentor, Not Monster
Yang Kita Dengar di Sekitar Kita
Seorang ibu mendapati anaknya terus-menerus mendapat nilai jelek di sekolah. Sang ibu berusaha mencari akar permasalahannya,
"Kenapa sih nilai kamu jelek-jelek terus. Coba cerita sama Mama, ada apa?"
Semua orangtua pasti setuju bahwa ini adalah langkah yang benar. Langkah yang benar adalah mengakui sebagai orangtua bahwa sang anak memiliki masalah. Langkah yang benar adalah mengajak anak mengakui, bahwa ia memiliki sebuah masalah. Kedua hal ini perlu digarisbawahi karena beberapa dari kita, dalam keseharian yang kita lihat di sekeliling kita, orangtua yang tidak bersedia mengakui kesalahan, apalagi memperbaikinya. Kita pasti pernah mendapati orangtua murid di sekolah anak yang menyalahkan guru atas sesuatu yang terjadi pada anaknya. Atau menyalahkan wasit saat anaknya kalah. Singkatnya, ketika sesuatu yang salah terjadi, yang salah itu seluruh dunia, bukan anaknya. Hari ini, anaknya adalah korban dari kebodohan guru. Kemarin, anaknya adalah korban dari ketidakadilan wasit. Tahun depan, anaknya adalah korban dari tidak sempurnanya sistem pendidikan.
Dunia salah.
Anaknya sempurna.
Jadi, orangtua yang mengakui anaknya memiliki masalah (ketika masalah datang) sudah selangkah lebih maju dari yang lain. Orangtua yang mengajak anaknya mengakui ada masalah – dan mencari akar masalah, sudah dua langkah lebih maju dari yang lain. Tapi kemudian, inilah yang mengerikan dari menjadi orangtua. Langkah berikutnya pun masih penuh perangkap di mana niat baik kita memotivasi anak, justru akan mematikan motivasi anak.
Saya Musuhmu
Dengan semua niat baik yang ada, sang ibu berusaha memotivasi sang anak.
"Kenapa kamu gak bisa seperti kakak kamu, yang pintar?"
"Kakak kamu nilainya bagus. Kenapa kamu jelek?"
"Si Robin, teman sebangkumu, nilainya bagus. Dia bisa, kamu juga harus bisa dong."
Dan di sini, banyak dari kita mulai masuk ke dalam perangkap tersebut.
Tidak usah anak. Kita pun akan gerah jika atasan kita membanding-bandingkan performa kita dengan kolega kerja yang lain. Kita akan langsung berkata, "Gak bisa gitu dong. Saya dan dia kan beda."
Sama saja dengan anak kita.
Perangkap lain adalah orangtua, menjadi monster kedua bagi si anak.
"Ayo, tunjukkan pada Bapak bahwa kamu bisa."
Yang sering kita lupa adalah, saat anak mendapat nilai buruk di sekolah, itu pun sudah menjadi sebuah monster baginya. Monster yang ia harus kalahkan. Jangan sampai ia pulang ke rumah dan mendapati monster yang sama. Sudahlah kita harus membuktikan diri kita di sekolah, sekarang kita sedang berusaha menyelesaikan masalahnya dengan menjadi monster kedua bagi dirinya. Dari persepsi anak kecil ini bukan solusi.
Saya Temanmu
Elisa Medhus dalam bukunya, Hearing is Believing, percaya dengan konsep I am your friend, not your enemy.

Ketika menemukan masalah pada anak, orangtua yang bijak akan mengakui adanya masalah tersebut. Kemudian, mengajak anak untuk juga mengakui masalah itu. Kemudian, menunjukkan bahwa kita berada di sampingnya, siap memberikan support kita untuk menyelesaikan masalah itu.
Daripada membandingkan anak dengan orang lain,
"Kakak kamu nilainya bagus. Kenapa kamu jelek?"
"Si Robin, teman sebangkumu, nilainya bagus. Dia bisa, kamu juga harus bisa dong."
... lebih baik dan lebih logis untuk mengajaknya membayangkan the bigger picture. Gambaran yang lebih luas.
"Nak, nilai matematika kamu 6. Ini Bapak lihat, nilai rata-rata di kelas kamu, 7,2. Kamu ketinggalan nih dari teman-teman kamu."
Ingat bahwa tidak ada anak (bahkan orang dewasa) yang dapat menerima dibanding-bandingkan dengan pribadi lain. Kenapa? Karena dalam konteks perbandingan pribadi, tidak ada dua anak yang sama. Seperti yang sudah dibahas di bab lain, mungkin Robin lebih pintar karena ia les matematika tambahan dan kita tidak memberikan hal yang sama pada anak kita. Mungkin kedua orangtua Robin memiliki IQ>130 sedang kita pun pas-pasan.
Sekali lagi, tidak ada anak yang menerima dibandingkan dengan anak lainnya. Tapi anak akan melihat ada sesuatu yang salah jika ia dibandingkan dengan satu populasi penuh.
Mungkin anak akan menolak dibandingkan dengan Robin yang lebih pintar. Tapi anak kita mungkin akan berpikir ulang jika ia menyadari bahwa nilainya lebih buruk dari Robin, Agus, Asep, Dadang, Marcel, Dewi dan 40 anak sebaya lainnya.
Anak juga memiliki sistem refleksi diri. Anak juga memiliki kemampuan untuk menakar dirinya dibanding teman-teman (majemuk).
Kalah dari Robin? Ya sudah lah memangnya kenapa? Lha wong memang Robin pintar.
Tapi kalah sama satu kelas? Waduh! Kalah sama Asep, Dadang dan Marcel? Mereka kan teman main bola saya. Kita sama-sama tidak belajar lho malah bermain bola seharian. Kok mereka masih bisa ya dapat nilai lebih bagus? Ada yang salah dengan diri saya! Saya yang harus berubah!
Ini juga berlaku untuk memotivasi anak lebih tinggi lagi. Berikan mereka the bigger picture.
"Nak, kamu nilai 7,6. Nilai rata-rata kelas 7,5. Kamu sama lah dengan semua anak dalam kelas. Tapi tahu gak, kalau kamu belajar 1 jam lebih lama setiap malam, Bapak yakin kamu akan bisa mendapat angka 9. Kamu akan lebih baik dari diri kamu kemarin dan lebih baik dari semua orang di dalam kelas. How cool is that?"
Satu lagi argumen tentang perbandingan. Membandingkan hanya akan valid, jika perbandingan dilakukan kepada 1 tolak ukur yang benar, netral, valid, dan umum.
"Anak seumur kamu biasanya cepet lho makan sendiri."
"Nilai rata-rata di kelas kamu ini, 7,3 lho."
Beberapa orangtua memandang adanya risiko,
"Jika dibandingkan dengan populasi, nanti anak saya merasa tolol dong."
Pertama, ya mungkin itu kenyataan yang harus kita hadapi.
Kedua, ya berarti itu tugas orangtua untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak.
"Nak, kamu bukan bodoh. Ini artinya kita (kamu dan ibu) harus menghabiskan waktu lebih banyak lagi belajar.
Ingat, tidak ada orang bodoh. Hanya ada orang yang belajar dan tidak belajar."
Langkah berikutnya, daripada memberikan ekspektasi.
"Tunjukkan pada bapak, bahwa kamu bisa."
Lebih baik memberikan dia keyakinan
"Ayuk. Mulai sekarang, setiap malam, kamu dan Bapak mengerjakan soal matematika ini sampai kamu bisa."
Pernahlah kita mendengar anak berujar,
"Gak mau ah, belajar sama Mama. Maunya diajarin Papa."
"Gak mau ah belajar tenis sama Papa. Maunya sama Abang yang itu.”
Ini terjadi karena orangtua, sadar atau tidak sadar, pada titik itu sudah berubah posisi dari mentor yang memberikan support, menjadi monster kedua yang harus dikalahkan.
Anak kita sedang memiliki masalah. Untuk beberapa masalah, orangtua memang sebaiknya membiarkan mereka menyelesaikan masalah itu sendiri (seperti menyelesaikan konflik dengan orang lain). Itu akan membuat mereka belajar dan tumbuh.
Tetapi untuk beberapa masalah lain, seperti ketinggalan akademik, skill mastery (latihan tenis, latihan bola, mengejar nilai matematika, mengejar nilai sekolah), memang pada tempatnya bagi orangtua untuk memberikan dukungan. Jangan menjadi monster kedua.
Become the mentor they need.
Not the monster they have to face.

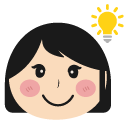




Asli keren banget ini artikelnya. Semoga kita sebagai orangtua tidak menjadi monster buat anak-anak kita ya.
Tfs kang Adhit! self reminder buat saya dan suami nih :)
Artikel yang keren banget! izin share ya Mas.
TFS ya kang Adhit..bener2 berkaca banget ama postingan ini.. :)
Ahhh masih suka terjebak di hal yabg sama, menjadi monster untuk anak sendiri... Terima kasih mas Adhit suadah diingatkan....