Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak
Mungkin ketidaksetaraan gender di negara kita tidak separah di negara lain. Sebut saja Pakistan yang dulu melarang perempuan mendapat pendidikan, atau di Arab Saudi yang dulu melarang perempuan untuk menyetir. Namun stereotype berbasis gender seperti ‘laki-laki tidak boleh cengeng seperti anak perempuan’ atau ‘perempuan harus lemah lembut’ masih sering didengar di kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidaksetaraan gender yang terjadi umumnya dimulai sedari dini, dari perbedaan pola asuh ke anak laki-laki dan anak perempuan.

(Gambar: www.pexels.com)
Padahal, menurut Konvensi Hak Anak PBB, setiap anak berhak untuk mendapatkan haknya tanpa memandang latar belakangnya, termasuk gender. Hak ini mencakup hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, mendapat perlindungan, belajar dan bermain, hingga hak untuk berkembang untuk mencapai potensi maksimalnya. Ketidaksetaraan gender pada pola asuh anak bisa berdampak pada ketidaksetaraan anak mendapatkan haknya, yang pada akhirnya mencelakai hak anak untuk berkembang maksimal sesuai potensinya.
Sebagai contoh, stigma bahwa perempuan itu harus dilindungi karena lebih rentan daripada laki-laki. Sehingga dalam pengasuhan, anak perempuan cenderung lebih dilindungi. Misalnya saja, anak perempuan lebih dikhawatirkan jatuh saat belajar jalan atau memanjat daripada anak laki-laki. Padahal, anak-anak punya hak yang sama untuk belajar dan mengeksplorasi. Sebenarnya anak mempunyai insting yang hebat untuk menyadari kapan mereka mampu mengerjakan hal sendiri dan kapan butuh bantuan. Tugas orangtua untuk mengasah insting tersebut. Kalau sering-sering dibantu, mereka bisa jadi merasa lemah dan mudah minta bantuan dalam segala hal. Kalau sering-sering dilarang, mereka bisa jadi mudah takut di kemudian hari.
Seorang psikolog dari Lawrence University, Peter Glick, juga menekankan bahwa stigma ‘perempuan harus dilindungi’ seharusnya dihilangkan. Sebaiknya, manusia (laki dan perempuan) harus melindungi mereka yang rentan (anak kecil, manula, dan lain-lain). Tidak semua laki-laki itu kuat. Tidak semua perempuan itu rentan. Semua perempuan harus bisa melindungi dirinya sendiri. Dan semua laki-laki juga demikian. Anak perempuan dan anak laki harus sama-sama bisa menjaga dan mempertahankan diri.
Anak juga mempunyai hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapatnya. Jadi adalah wajar kalau anak laki-laki menangis dan anak perempuan marah untuk mengekspresikan emosinya. Toh semua emosi ini manusiawi dan wajar dirasakan siapa aja. Para psikolog bahkan menyarankan agar anak terbiasa mengeluarkan emosinya, karena berdampak positif pada tumbuh kembang anak. Hal ini membantu anak berempati dengan mengenali emosi orang lain. Selain itu, saat anak bisa mengekspresikan emosinya, orang tua jadi bisa memberikan dukungan yang memang dibutuhkan anak.
Sebaliknya, ada studi yang membuktikan bahwa anak yang tidak bisa mengekspresikan emosinya, lebih besar kemungkinannya mengalami depresi. Dampak buruknya, depresi ini bisa memicu untuk melakukan kekerasan fisik saat dewasa. Seorang Developmental Psychologist dari University of Kentucky, Christia Brown, mengatakan bahwa remaja laki yang 'terpaksa' memenuhi tuntutan stereotype untuk 'bersikap seperti laki-laki', ada kecenderungan melakukan bullying untuk menunjukkan 'kejantanannya', agar mereka sendiri tidak menjadi korban bullying.
Karena selain menjaga anak perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan, penting juga untuk menjaga anak laki agar tidak menjadi pelaku kekerasan. Begitu pula sebaliknya.
Selain itu, kita juga terbiasa mengidentifikasikan mainan anak dengan gender. Pertanyaannya, kenapa harus heran lihat anak perempuan main pesawat-pesawatan, tapi berdecak kagum melihat pilot perempuan? Kenapa harus heran lihat anak laki main masak-masakan, tapi berdecak kagum melihat koki laki-laki? Bukankah semua mainan ada fungsinya masing-masing? Mengotakkan mainan anak sesuai gender sama dengan membatasi pilihan anak untuk bermain. Padahal anak punya hak untuk bermain tanpa terbatas pada gendernya. Hal yang penting, orang tua dampingi anak saat bermain agar anak dapat merasakan manfaat bermain dengan maksimal.
Kesetaraan gender dalam pengasuhan anak juga perlu didukung oleh peran orang tua yang seimbang. Alih-alih ayah memposisikan diri dominan dan istri di posisi inferior, lebih baik memposisikan hubungan secara seimbang sebagai pasangan dan orang tua untuk anak. Menunjukkan peran ayah-ibu yang seimbang menjadi awal mematahkan stereotype berbasis gender. Selanjutnya adalah mengajarkan anak untuk melakukan pekerjaan rumah secara adil dan seimbang juga, tanpa berdasar gender. Misalnya, tidak masalah mengajak anak laki-laki mengepel rumah dan anak perempuan mencuci mobil. Karena skill mengerjakan pekerjaan rumah sama-sama bermanfaat untuk anak laki-laki dan anak perempuan di kemudian hari.
Sebagai tambahan, penting juga untuk tidak menjadikan gender sebagai alasan perilaku anak. Seperti misalnya, “Anak perempuan kok suka main pukul kaya anak laki” atau “Anak laki kok penakut kaya anak perempuan”. Anak-anak lahir sebagai blank state atau ‘kertas putih yang polos’ dengan pemahaman bahwa semua manusia itu sama, semua gender itu setara. Mereka lahir dengan tidak punya pikiran bahwa satu gender lebih baik dari gender lainnya. Tinggal selanjutnya, bagaimana kita sebagai orangtua menanamkan konsep kesetaraan gender pada anak-anak kita.
Alih-alih memaksakan ajaran “Laki-laki harus begini” dan “Perempuan harus begitu”, lebih baik fasilitasi anak untuk tumbuh sebagai manusia, as a human being.

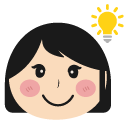




Susah memang mengasuh dua anak beda gender, apalagi yang jarak umurnya deketan. Biasanya kalo udah mentok, aku konsul sama psikolog anak dan orangtua di sana. Biar nggak sampe salah langkah gitu. Bagiku konsul ke psikolog penting, karena nggak semua hal bisa kita pikirkan sendiri.